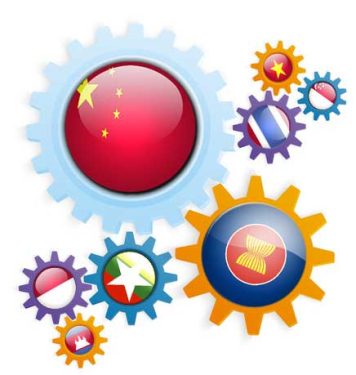Setelah satu dekade berlalu dengan tenang, konflik Laut Cina Selatan muncul kembali sebagai topik utama dalam perdebatan tentang isu keamanan di Asia Timur. Dilihat dari berbagai sudut pandang, konflik ini merupakan ujian yang menentukan (litmus test) bagi hubungan Cina dengan ASEAN dan negara-negara anggotanya. Konflik Laut Cina Selatan merupakan bagian yang tak terpisahkan, dan merupakan satu perwujudan dari hubungan yang mendasar tersebut. Jika kedua pihak tidak dapat mengatasi konflik Laut Cina Selatan, lalu apa yang akan tersisa sebagai hasil penerapan kebijakan “keterlibatan positif” (positive engagement) selama dua dekade di bawah payung diplomasi “soft power” dan “constructive engagement” (keterlibatan yang setara)?
Meskipun situasi di Laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian belakangan ini, isu tersebut sebenarnya bukan barang baru. Di awal 1990-an topik tersebut telah diperkirakan khususnya oleh para analis Amerika, akan menjadi konflik yang tak berkesudahan. Dilihat secara sepintas, situasi saat ini mungkin mirip dengan situasi pada era 1990-an. Akan tetapi, ketika diperhatikan dengan lebih mendalam, sangat jelas bahwa kondisi sebenarnya berbeda. Perubahan-perubahan besar telah terjadi di dalam hubungan Cina dan ASEAN, begitu pula di dalam sistem regional semenjak awal 1990-an. Secara keseluruhan, telah terbentuk suatu hubungan yang positif dan konstruktif di antara Cina dan ASEAN, khususnya di bidang ekonomi yang telah mengubah berbagai aspek menyangkut dinamika politik, ekonomi, sosial, dan keamanan di kawasan tersebut. Semua perubahan ini tidak bersifat sementara, tetapi akan terus-menerus mempengaruhi perilaku para pihak terhadap satu sama lain, termasuk di dalam lingkup konflik Laut Cina Selatan.
Diplomasi “soft power” dan kebijakan “constructive engagement”
Salah satu faktor paling penting di balik pertanyaan “bagaimana Cina dan ASEAN telah berhasil mengembangkan hubungan semenjak akhir Perang Dingin” adalah upaya yang ditempuh oleh kedua belah pihak dengan mendayagunakan sumber-sumber “soft power” yang mereka miliki dalam mendekati pihak yang lain. Cina telah mencoba untuk menghapus persepsi tentang Cina sebagai ancaman di Asia Tenggara dengan membentuk (ulang) keberpihakan negara-negara Asia Tenggara terhadap Cina menggunakan diplomasi “soft power,” sementara ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara telah menerapkan strategi “constructive engagement” terhadap Cina sebagai upaya untuk membuat Cina terlibat di dalam organisasi regional dan meyakinkan Cina untuk menerima sejumlah norma-norma regional dan kebiasaan-kebiasaan regional, seperti keterlibatan secara multilateral dan “cara ASEAN” (ASEAN way).
Tetapi tidak dikenal adanya kesepakatan tentang definisi “soft power” dalam konteks ‘soft power’ Cina. Definisi ketat “soft power” yaitu “kemampuan untuk memperoleh apa yang dikehendaki dengan menggunakan daya pikat dibandingkan dengan menggunakan ancaman atau uang” dan “kemampuan untuk membentuk keberpihakan seseorang” 1 – definisi ini sangat problematik untuk diterapkan dalam konteks Cina. Ada beberapa alasan di balik hal tersebut, termasuk di dalamnya yaitu bahwa sumber daya ekonomi Cina merupakan ciri mendasar dari kekuatan Cina dan menjadi kunci kesuksesan diplomasi dan daya tarik Cina (sesuai dengan pandangan Nye tentang “hard power”), bahwa kepemimpinan Cina merupakan istilah yang sesuai ketika mereka menganggap bahwa hal tersebut menguntungkan bagi pembentukan Cina yang berkuasa, dan sebagai topik yang berbeda tentang “soft power” telah muncul di Cina (yaitu “soft power” dengan ciri Cina). Saya tidak berniat memecahkan persoalan definisi yang problematik tersebut di dalam tulisan ini, tetapi saya hanya akan memusatkan perhatian pada bentuk-bentuk “soft power” yang diterima dan dianut oleh pemerintah Cina dan Asia Tenggara; daya tarik suatu negara berbeda-beda di mata pengamat yang berbeda.
Kerjasama, optimisme dan institusionalisasi dari hubungan yang damai
Di awal 1990-an Cina menerapkan suatu strategi pasca Perang Dingin yang baru, bercirikan kebijakan “good neigbourhood” (bertetangga yang baik), yang bertujuan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai model strategi bagi “kebangkitan Cina yang damai” (peaceful rise). Pada saat yang sama, ASEAN juga menjalankan suatu kampanye diplomatik untuk melibatkan diri, daripada mengisolasi, dengan Cina. Oleh karena itu, ada suatu proses timbal balik di antara strategi “constructive engagement” ASEAN dan pengadopsian diplomasi “soft power” oleh Cina untuk menepis persepsi tentang Cina sebagai ancaman. Pemulihan hubungan baik di antara Cina dan ASEAN ini akan menjadi proses perubahan-identitas dalam jangka waktu panjang bagi kedua belah pihak, yang telah menafsirkan ulang kepentingan-kepentingan mereka dan mengubah cara mereka bersikap terhadap satu sama lain. Pemulihan hubungan baik ini merupakan hal yang mendasar dalam memahami mengapa Cina dan ASEAN telah berupaya untuk memelihara hubungan mereka dalam cara yang konstruktif dan damai dan mengapa hubungan di antara Cina dan ASEAN tersebut telah berkembang menuju arah yang positif, termasuk di dalamnya mengenai Laut Cina Selatan. 2
Seiring dengan berjalannya waktu, khususnya semenjak 2000, Cina telah beralih peran dari sekedar peserta menjadi tokoh proaktif di dalam lingkup multilateral. Alasannya adalah pemahaman tentang Cina dan maksud-maksud yang terkandung dari tindakan Cina yang tidak berbahaya itu akan mengubah pandangan dan kepentingan para aktor lainnya di Asia dan dengan demikian, akan menguntungkan Cina. Selama ini kerjasama multilateral dengan Cina sering terinstitusionalisasikan sesuai dengan cara yang diinginkan oleh ASEAN.
Penerimaan Cina terhadap multilateralisme dan institusionalisasi atas hubungan damai telah menciptakan suatu kerangka struktural dalam berbagai forum, dialog, dan norma-norma serta praktek-praktek diplomatik yang diterima. Institusionalisasi merupakan suatu bagian penting dari upaya ASEAN untuk melibatkan diri dengan Cina dan membantu untuk meningkatkan keuntungan di dalam perdamaian dan stabilitas regional. Lebih jauh lagi, hal ini juga menjamin bahwa Cina tidak akan menjadi ancaman seperti yang selama ini ditakutkan. Tujuan jangka panjang dari upaya untuk melibatkan Cina, adalah untuk mengunci Cina di dalam suatu institusi multilateral dalam skala regional, yang tidak hanya memoderisasi tetapi juga mengubah perilaku Cina secara regional, 3 telah berhasil dicapai sedikit demi sedikit: perilaku Cina telah menjadi lebih moderat, dan Cina telah menjadi terbiasa untuk, dan menurut dengan, keterlibatan di dalam forum multilateral. Lebih jauh lagi, Cina juga menerima “cara ASEAN” sebagai prinsip diplomatik dan juga telah memulai untuk memberi perhatian terhadap kepentingan negara-negara tetangganya. Ini merupakan proses timbal balik di antara diplomasi “soft power” Cina dan kebijakan politik “constructive engagement” ASEAN.
Pada saat yang sama, karena adanya hubungan yang baik dan penerimaan Cina atas multilateralisme termasuk juga kesediaan Cina untuk terlibat dengan ASEAN sebagai satu kesatuan, muncul satu asumsi di kalangan analis bahwa Cina akan bersikap agresif dan konflik Laut Cina Selatan akan menajdi konflik yang tak berkesudahan. Meski demikian, semenjak pertengahan 1990-an terlihat adanya penurunan ketegangan di dalam konfilk SCS. Salah satu kunci penting di balik hal tersebut adalah pernyataan Cina sebelum berlangusngnya Forum Regional ASEAN (ARF) di tahun 1995 berkaitan dengan keinginan Cina untuk mendiskusikan masalah Spratly dalam latar multilateral. Dua tahun kemudian, konflik Laut Cina Selatan bahkan dimasukkan dalam agenda ARF. Ini merupakan hal yang penting dalam proses yang berujung pada “Deklarasi Pernyataan Sikap Para Pihak yang terlibat di Laut Cina Selatan (Declaration on the Conduct of Parties in the South Cina Sea) di tahun 2002.
Sikap baru Cina yang tegas
Situasi berubah di tahun 2007 seraya Cina mengadopsi kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Nyatanya, Cina telah memperluas jangkauan militernya, mengukuhkan klaim yurisdiksi di wilayah Laut Cina Selatan, dan menganut kebijakan yang lebih keras guna meremehkan berbagai klaim yang telah diajukan oleh negara-negara lain. Dengan alasan-alasan mendasar yang dapat ditelusuri pada peningkatan kemampuan dan kepercayaan diri Cina, penguatan nasionalisme serta berkembangnya rasa tidak puas Cina atas campur tangan pihak asing di dalam konflik Laut Cina Selatan, sebagian besar dari legitimasi diplomasi “soft power” Cina hancur di dalam waktu yang singkat. Legitimasi tersebut bahkan menjadi lebih lemah lagi di tahun 2010 dengan adanya provokasi politik dan militer antara Washington dan Beijing saat Cina menyatakan Laut Cina Selatan sebagai salah satu kepentingan utama layaknya Tibet dan Taiwan dan mengadakan latihan militer di wilayah tersebut. Situasi menjadi semakin tegang seraya Cina semakin tegas menyatakan klaimnya di Laut Cina Selatan.
Dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, harus ditekankan di sini bahwa sikap tegas yang diambil oleh Cina bukanlah suatu kejutan bagi ASEAN (bertentangan dengan reaksi negara-negara Barat). Negara-negara anggota ASEAN tidaklah tertipu dengan “serangan daya pikat” (charm offensive) Cina seperti yang telah dilansir oleh sebagian analis. Sebaliknya, mengutip pernyataan Dewi Fortuna Anwar, negara-negara anggota ASEAN “telah dan senantiasa waspada terhadap janji-janji dan bahaya-bahaya inheren yang ditunjukkan Cina” dan percaya bahwa “jalan terbaik dalam berhubungan dengan Cina adalah dengan melibatkan dan mengintegrasikan Cina secara menyeluruh dalam tatanan regional.” 4
Sinyal beragam dari Beijing
Selama tiga tahun terakhir, telah muncul sinyal beragam dari Beijing. Di satu sisi, berbagai langkah telah ditempuh untuk melunakkan sikap Cina. Cina telah menerima berbagai pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan Declaration of Conducts (DOC) tahun 2002 yang diusulkan ASEAN. Suatu upaya diplomatik untuk meyakinkan dunia atas niat damai Cina telah dimulai, termasuk di dengan terbitnya buku putih (white paper) pada 6 September 2011 yang menegaskan bahwa Cina akan mengikuti petunjuk Deng Xiaoping dan akan mengeyampingkan pertentangan di Laut Cina Selatan guna bekerjasama dalam pembangunan.
Pada sisi yang lain, Cina telah berupaya dalam memecah belah ASEAN dengan membujuk Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand untuk tidak membicarakan konflik Laut Cina Selatan. Itikiad baik Cina sebenarnya juga dapat dipertanyakan. Sebagai contoh, setelah Filipina dan Cina menemui jalan buntu pada tahun 2012 soal beting Scarborough (Shoal Scarborough), Cina tidak mematuhi kesepakatan lisan untuk angkat kaki bersama-sama dari wilayah tersebut. Cina justru menutup mulut laguna tersebut untuk mencegah kembalinya aparat Filipina dan menyelenggarakan patroli di sekitar beting Scarborough. Ini hanya merupakan satu contoh.
Meski demikian, ada upaya untuk menguatkan kerjasama dan mengembalikan kepercayaan yang hilang itu saat Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang mengunjungi Asia Tenggara bulan Oktober tahun lalu. Xi mengusulkan untuk mempererat hubungan Cina-ASEAN dengan membentuk suatu “komunitas dengan tujuan bersama” (community of common destiny). Perdana Menteri Li juga berupaya dengan menegaskan bahwa Cina dan ASEAN seharusnya mempromosikan “kehidupan bertetangga dan kerjasama yang bersahabat antara Cina dan negara-negara ASEAN.”
Kesimpulan – dan menuju ke hal yang tidak diketahui
Selama periode 1989-2007 terlihat dengan jelas adanya efek yang positif dan nyata dari pendekatan “soft power” yang ditempuh kedua belah pihak. Akan tetapi, meskipun mungkin telah ada efek yang nyata, daya tahan “soft power” untuk jangka waktu panjang sepertinya kurang jelas. Pada saat ini, seraya niat Cina telah dipertanyakan, dampak dari diplomasi “soft power” Cina di Asia Tenggara sangat terbatas. Kepercayaan yang dibangun dengan susah payah sebagian besar telah hancur semenjak 2007. Cina menyadari hal ini dan telah berupaya untuk berubah guna merebut kembali kepercayaan yang telah hilang. Akan tetapi, sangat diragukan hal ini akan berhasil, terlepas dari upaya-upaya yang dilakukan Cina. Keterlibatan ASEAN telah menjadi lebih pragmatis, dengan penekanan lebih pada penyetaraan secara halus (soft balancing), atau pemagaran (hedging), terhadap Cina. Negara-negara anggota ASEAN sendiri telah menjadi terbagi-bagi tentang bagaimana seharusnya konflik Laut Cina Selatan diselesaikan (apakah secara multilateral atau bilateral); hal ini dapat melemahkan kemungkinan berhasilnya “constructive engagement” yang hendak dicapai. Akan tetapi, telah ada dampak mendasar dari “constructive engagement” tersebut. Penerimaan Cina secara umum dan institusionalisasi dari “cara ASEAN” serta penerimaan atas institusi-institusi yang digerakkan oleh ASEAN terus-menerus berlangsung, dan hal ini mengakibatkan perubahan yang melibatkan berbagai gagasan dan norma yang telah terjadi.
Keterlibatan secara positif melalui diplomasi “soft power” secara timbal balik bukannya tidak berguna. Keterlibatan secara positif telah berkontribusi terhadap pembentukan hubungan regional yang positif secara keseluruhan, menciptakan ruang bagi pertumbuhan ekonomi Cina dan Asia Tenggara pada saat yang bersamaan. Seandainya saja tidak ada keterlibatan secara timbal balik dengan pendekatan “soft power,” situasi di Asia Timur akan terlihat sangat jauh berbeda sekarang. Sebuah tatanan regional yang baru telah terbentuk melalui berbagai upaya oleh kedua belah pihak untuk bersosialisasi satu sama lain. Hubungan-hubungan yang dinormalisasi telah dipertahankan. Cina tetap terus melibatkan diri dalam organisasi-organisasi regional dann internasional yang dipimpin oleh ASEAN dan mempromosikan model-model mereka sendiri. Lebih jauh lagi, tatanan tersebut telah terbentuk di atas nilai-nilai bersama, yang merupakan nilai-nilai regional, bukan nilai-nilai yang dipaksakan secara eksternal.
Mikael Weissmann
Peneliti, Swedish Institute of International Affairs
(Diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh Michael Andreas Tandiary)
Kyoto Review of Southeast Asia. Issue 15 (March 2014). The South China Sea
Notes:
- Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, 1st ed. (New York: Public Affairs, 2004), x, 5 ↩
- Mikael Weissmann, “The South China Sea Conflict and Sino-Asean Relations: A Study in Conflict Prevention and Peace Building,” Asian Perspective34, no. 3 (2010); The East Asian Peace: Conflict Prevention and Informal Peacebuilding (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012); “Why Is There a Relative Peace in the South China Sea?,” in Entering Uncharterd Waters? Asean and the South China Sea Dispute, ed. Pavin Chachavalpongpun (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014) ↩
- Daojiong Zha and Weixing Hu, Building a Neighborly Community: Post-Cold War China, Japan, and Southeast Asia (Manchester: Manchester University Press, 2006), 121-2. ↩
- Dewi Fortuna Anwar, “Between Asean, China and the United States,” Jakarta Post, 30 August 2010 ↩