
Keberhasilan kampanye Bela Islam dalam menentang mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (atau ‘Ahok’) adalah bukti absah kebangkitan Islamisme di Indonesia pasca-Reformasi, yang sayangnya tidak dijelaskan dengan cukup memadai dalam kajian mengenai Islam di Indonesia akhir-akhir ini. Pertumbuhan Islamisme di Indonesia, terlepas dari transisi demokrasi selama dua dasawarsa, menunjukkan banyak cendekiawan dan pengamat masih lemah dalam menimbang pengaruh gerakan Islamis konservatif dan garis keras di Indonesia pasca-Reformasi. Dalam esai ini, saya berpendapat bahwa hal ini dapat dikaitkan dengan dominasi tesis “Civil Islam” (Islam Sipil atau Islam Berkeadaban)—yang diperkenalkan oleh Robert Hefner dalam magnum opusnya, Civil Islam (2000; edisi terjemahan diterbitkan oleh ISAI, tahun 2001)—yang terbit sesaat setelah Reformasi di Indonesia pada 1998. Tesisnya segera menjadi kerangka kerja utama yang dipergunakan oleh banyak cendekiawan dan penyusun kebijakan dalam melihat Islam di Indonesia selama periode pasca-Reformasi.
Hefner mendefinisikan Islam Sipil sebagai “berbagai etika publik yang dikembangkan oleh pemikir, penggiat, dan organisasi-organisasi Muslim di Indonesia dan di beberapa negara dengan mayoritas Muslim, yang bercita-cita untuk menyirapkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan dalam Islam dengan nilai-nilai demokratis” (Hefner 2017, hal. 7). Hal ini diartikulasikan oleh para intelektual Islam Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Dawam Rahardjo, dan Abdurrahman Wahid. Para pemikir ini berhasil menggabungkan teologi Islam klasik dan teori sosial Barat untuk menghasilkan uraian mengenai masyarakat Indonesia selama masa Orde Baru. Uraian-uraian ini dirancang untuk mereformasi Islam Indonesia, untuk menarik jarak dari gagasan Indonesia sebagai negara Islam, sebuah gagasan yang ditawarkan oleh para pendahulu mereka yang konservatif, dan untuk memperbarui pemikiran Islam klasik demi menunjukkan kesesuaiannya dengan gagasan-gagasan modern seperti demokrasi, pluralisme, dan toleransi.
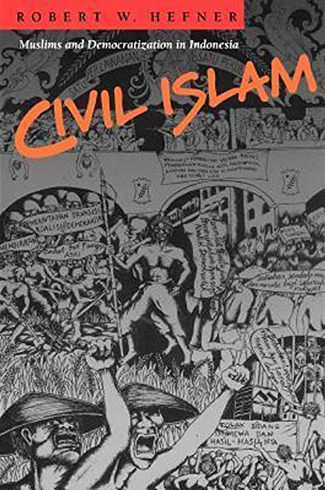
Akan tetapi, dua dasawarsa setelah Reformasi, visi yang diperkirakan oleh para pendukung tesis “Civil Islam” ini—bahwa sebagian besar masyarakat Islam Indonesia adalah orang-orang moderat dan cocok dengan nilai-nilai demokrasi liberal seperti adanya penghargaan atas hak asasi manusia, pluralisme, dan toleransi beragama—menjadi semakin sukar dipahami, sebagaimana riset menunjukkan Islam Indonesia justru tumbuh menjadi lebih konservatif (van Bruinessen 2013) dan semakin tidak toleran terhadap ekspresi keagamaan yang bertentangan dengan arus utama keyakinan Islam (Menchik 2016). Lebih memprihatinkan lagi, ekspresi-ekspresi itu tidak hanya diungkapkan oleh kelompok-kelompok Islamis baru seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Hisb-ut Tahrir Indonesia (HTI), tetapi juga oleh banyak ulama dan penggiat dalam NU dan Muhammadiyah. Seperti yang saya jelaskan di sini, Islamis—didefinisikan sebagai “Muslim yang menjalankan tindakan politik untuk menerapkan apa yang mereka anggap sebagai agenda Islam” (Piscatori 2000, hal. 2)—semakin mendominasi masyarakat dan politik Indonesia selama dua dasawarsa terakhir.
Saya berpendapat bahwa para pendukung tesis “Civil Islam” gagal dalam memperkirakan empat perkembangan Islam di Indonesia pasca-Reformasi. Pertama, para pendukung tesis “Civil Islam” adalah intelektual Muslim Indonesia elite yang juga fasih dalam teori sosial Barat. Tafsir mereka tentang bagaimana Islam dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai liberal seperti pluralisme dan toleransi dapat diikuti dengan mudah oleh para akademisi dan pengamat Barat. Selain Hefner, sejumlah cendekiawan memuji keutamaan-keutamaan Islam neo-modernis dan Islam Indonesia moderat selama paruh akhir rezim Suharto dan periode awal Reformasi (mis. Barton dan Fealy 1996, Liddle 1996).
Namun, tafsir semacam itu kerap tidak sesuai dengan para ulama dan penggiat arus utama NU dan Muhammadiyah, yang mendominasi kepemimpinan organisasi-organisasi ini di tingkat akar rumput. Mayoritas ulama Islam menyelesaikan studi di sekolah-sekolah Islam tradisional (pesantren salaf), yang lebih banyak mengembangkan pemahaman harfiah tentang Islam dalam kurikulumnya, dan lulusan pesantren ini cenderung menjadi ulama Islam (kyai) dan penceramah dalam komunitas setempat mereka (Sakai dan Isbah 2014). Pemahaman konservatif tentang Islam ini mungkin menjelaskan mengapa para ulama ini cenderung memiliki tafsir yang seadanya dan bersyarat tentang toleransi dibandingkan dengan yang dibagikan oleh para intelektual Islam berpendidikan Barat yang mendukung wacana “Civil Islam” (Menchik 2016). Hal ini pada gilirannya, menjelaskan mengapa banyak ulama bersedia untuk membiarkan dan terkadang mengembangkan tindakan penganiayaan terhadap minoritas kepercayaan seperti komunitas Ahmadiyah dan Muslim Syiah (Hamayotsu 2018) atau mendukung unjuk-rasa Bela Islam menentang Ahok.

Kebangkitan Otoritas Islam Baru
Kedua, pendukung tesis “Civil Islam” gagal mengantisipasi kemandekan lebih lanjut dari otoritas Islam tradisional di Indonesia pasca-Reformasi, yang disertai dengan munculnya tokoh-tokoh otoritas alternatif Islam baru seperti penceramah di televisi, ustadz populer, dan penceramah daring. Contoh tokoh-tokoh otoritas Islam baru ini adalah Abdullah Gymnastiar, Yusuf Mansur, Bachtiar Nasir, dan Felix Siauw, yang popularitasnya dapat dikaitkan dengan fenomena ini. Para penceramah ini cenderung menggunakan tafsir-tafsir ideologi Islam yang lebih konservatif, dan mengembangkan hubungan dekat dengan tokoh agama lainnya dari kelompok Islamis garis keras. Misalnya, Gymnastiar menjalin hubungan erat dengan pemimpin spiritual FPI Habib Rizieq Shihab dan pendiri JI Abu Bakar Basyir dan memberikan ceramah dalam unjuk-rasa politik yang diselenggarakan oleh HTI (Hoesterey 2016, hal. 45 dan 198). Sementara itu, Bachtiar Nasir mengembangkan jaringan dengan lulusan pesantren Gontor tempatnya menempuh pendidikan, bersama dengan para penggiat Muhammadiyah yang lebih konservatif, yang bersama-sama memainkan peran penting selama unjuk-rasa Bela Islam (IPAC 2018).
Keterkaitan para penceramah populer dengan kelompok Islam konservatif dan garis keras ini menjelaskan mengapa mereka dapat dengan mudah digerakkan dalam aksi-aksi massa bersama seperti unjuk rasa Bela Islam yang didukung oleh kelompok-kelompok garis keras tersebut. Lebih penting lagi, munculnya penceramah di televisi, penceramah populer, dan tokoh-tokoh otoritas lainnya, semakin mengurangi otoritas ulama Islam tradisional yang diwakili oleh para ulama NU dan Muhammadiyah, yang tiba-tiba mendapati organisasi dan gagasan-gagasan mereka kehilangan relevansi, terutama di kalangan kaum muda Muslim kelas menengah.
Bahkan di dalam kelompok-kelompok moderat seperti NU, ulama yang tampil yang memperoleh pengikut secara luas cenderung mereka yang muda, kyai berpendidikan Timur Tengah dengan tafsir teologis yang lebih konservatif yang menolak prinsip-prinsip moderat, pluralis, dan inklusif yang pernah disokong oleh Abdurrahman Wahid dan ulama-ulama lainnya di dalam NU dengan kecenderungan moderat. Mereka termasuk Idrus Ramli, Buya Yahya, dan Abdul Somad, yang mendirikan “NU Garis Lurus” sebagai sebuah kelompok yang berusaha mengurangi teologi progresif dan pluralis yang dilembagakan oleh Abdurrahman Wahid dan juga didukung oleh Ketua NU saat ini Said Aqil Siradj, yang sekarang dikenal sebagai Islam Nusantara. Fakta bahwa ulama muda yang berafiliasi dengan NU Garis Lurus merupakan penceramah tradisionalis yang paling populer hari ini berpotensi mengacaukan prospek masa depan NU sebagai organisasi Islam moderat dan pluralis sebab kemungkinan besar mereka adalah calon pemimpin masa depan dalam organisasi Islam Indonesia.
Ketiga, para Islamis konservatif dan garis keras lebih cerdik daripada rekan-rekan moderat mereka dalam menyebarkan gagasan di pasar gagasan yang semakin bebas dalam era pasca-Reformasi Indonesia yang demokratis ini. Satu cara yang berhasil secara efektif dipergunakan kelompok garis keras dalam mempromosikan gagasan-gagasan mereka untuk memenangkan anggota baru adalah organisasi dakwah kampus. Organisasi pembiakan Islamis ini didukung oleh Gerakan Tarbiyah—kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan HTI dengan cepat tumbuh selama tahun 1980-an dan 1990-an, lantaran sifat organisasi mereka yang kecil dan bersifat rahasia membantu mereka lolos dari pengawasan ketat aparat keamanan Suharto (Arifianto 2018, hal. 6). Mereka mendapatkan popularitas karena kaum muda Muslim dari latar belakang Islam yang relatif sekular dan tidak salih mulai mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam dengan menghadiri acara-acara dakwah yang didukung oleh organisasi-organisasi ini.
Setelah periode pasca-Reformasi, kelompok-kelompok dakwah kampus Islamis semakin menggunakan posisi dominan mereka di universitas-universitas negeri sebagai wahana untuk mengubah pola pikir kaum muda Muslim Indonesia guna mendukung tafsir yang lebih eksklusif tentang Islam. Kelompok-kelompok seperti HTI berkembang di universitas-universitas negeri pendidikan guru (sebelumnya Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan—IKIP), mereka menargetkan para siswa yang akan menjadi guru sekolah menengah umum sebagai kadernya (Arifianto 2018, hal. 13). Banyak dari guru-guru ini agaknya berhasil menyampaikan tasfir-tafsir eksklusif tersebut di antara murid-murid mereka. Hal ini nampak dalam jajak pendapat baru-baru ini yang menunjukkan bahwa satu dari empat siswa sekolah menengah umum di Indonesia mengungkapkan dukungan mereka atas gagasan kekhalifahan Islam yang secara teratur dipromosikan oleh HTI (The Jakarta Post 2017).
Dakwah kampus hanyalah salah satu cara yang digunakan oleh kelompok garis keras untuk menyebarluaskan gagasan eksklusif mereka kepada para pengikut potensial. Berbagai kelompok Islam yang berafiliasi dengan Tarbiyah, HTI, dan gerakan Jama’ah Tabligh juga aktif mendukung bentuk-bentuk baru dakwah, mulai dari kegiatan dakwah Jumat di lembaga-lembaga besar negara, perusahaan, dan pusat perbelanjaan (Tempo 2017, hal. 64-65). Situs internet dan media sosial telah menjadi saluran baru bagi kelompok garis keras untuk menyebarkan pesan mereka selama dasawarsa terakhir ini, seperti melalui Arrahmah.com dan VOAIslam.com dan situs-situs lainnya yang semakin populer di kalangan pengguna internet yang mencari konten religius. Situs-situs ini menawarkan tafsir harfiah dan ortodoks tentang Islam yang disampaikan dengan cara yang jelas dan sederhana—kerap dalam dua-tiga menit saja—oleh para penceramah Islamis yang mengkhususkan diri dalam dakwah daring seperti halnya ustadz Khalid Basalamah. Keberhasilan kelompok-kelompok ini dalam mengakali rekan-rekan moderat mereka melalui kendali mereka atas internet serta media penyampaian yang lebih konvensional seperti dakwah kampus—membantu menjelaskan mengapa lebih banyak Muslim Indonesia, terutama generasi muda kelas menengah, mengikuti tafsir yang lebih konservatif tentang Islam dibandingkan para pendahulu mereka.

Aliansi yang Tidak Suci
Keempat dan terakhir, pendukung tesis “Civil Islam” mengesampingkan pertumbuhan aliansi antara politisi elite tingkat atas dengan ulama yang berafiliasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), baik di tingkat nasional maupun lokal. Para ulama dan politisi elite ini memihak pada kelompok-kelompok Islam garis keras seperti FPI untuk memenuhi ambisi mereka (Hadiz 2016, Hamayotsu 2018). Jelas ada upaya ekstensif dari kelompok Islam garis keras untuk mengembangkan aliansi dengan politisi, pegawai negeri, dan pejabat keamanan yang bersimpati dengan agenda mereka atau setidaknya ingin memanfaatkan dukungan mereka untuk mengembangkan tujuan politik mereka.
FPI telah mengembangkan jaringan dengan para petinggi sejak lembaga ini didirikan pada awal 2000-an. Panglima TNI (Purnawirawan) Wiranto (sekarang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) dan Komjen Pol Nugroho Djajusman dianggap sebagai kepala pelindung organisasi ini selama tahun-tahun awal berdirinya (Wilson 2015). Keterkaitan ini dipertahankan oleh pengampu kepemimpinan TNI dan Polri saat ini. Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang baru saja diganti, dilaporkan memiliki hubungan dekat dengan Habib Rizieq dan pemimpin senior FPI lainnya (McBeth 2017). Di tingkat regional, FPI mengembangkan hubungan yang ekstensif dengan pihak kepolisian daerah dan para komandan TNI juga, yang dilaporkan membantu untuk menghindari tuntutan hukum setiap kali mereka melancarkan serangan atas kelompok minoritas agama yang mereka targetkan.
Para elite ini semakin membentuk aliansi oportunistik dengan kelompok-kelompok ini begitu mereka menyadari kekuatan dan pengaruh kelompok Islam garis keras yang berkembang terutama selama musim pemilihan umum—demi memenangkan dukungan mereka dan menjangkau para anggotanya sebagai pendukung potensial mereka. Namun, aliansi antara Islamis, para ulama MUI, dan politisi elite ini telah menciptakan sejumlah kemunduran bagi prospek jangka panjang Islam moderat di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari diberlakukannya sekitar 440 peraturan syariah lokal di lebih dari 100 wilayah Indonesia (Pisani dan Buehler 2017) sejak Indonesia memulai desentralisasi politik pada 2001. Di tingkat nasional, undang-undang moralitas publik yang baru telah disetujui atau sedang dipertimbangkan oleh dewan legislatif. Contohnya, UU Anti-pornografi 2006 dan pasal-pasal pengantarnya dalam revisi KUHP yang akan disahkan oleh DPR beberapa waktu sebelum masa jabatan mereka berakhir di tahun 2019, akan sangat mengkriminalisasi hubungan seksual di luar pernikahan (Peterson 2018). Dengan perkembangan ini, prospek prinsip-prinsip dan wacana Islami yang berlaku dalam demokrasi Indonesia pasca-Reformasi menjadi semakin sulit dipahami hampir duapuluh tahun setelah hal-hal tersebut kali pertama dijabarkan.
Sementara beberapa cendekiawan (misalnya, Qurtuby 2018) tetap optimis akan prospek masa depan Islam moderat sipil di Indonesia, berdasarkan pengamatan di atas, kita tidak bisa lagi melihat “Civil Islam” sebagai wacana teologis paling dominan dalam Islam Indonesia. Meski prospek Islamisasi di Indonesia masih terdengar asing, hal ini tidak dapat dikesampingkan sepenuhnya dalam iklim meningkatnya Islamisme di Indonesia. Keberhasilan para Islamis dalam menggelar unjuk-rasa Bela Islam menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak bisa lagi diabaikan dalam analisis kontemporer politik Indonesia.
Alexander R. Arifianto
Research Fellow, Indonesia Programme
Rajaratnam School of International Studies
Universitas Teknologi Nanyang (NTU), Singapura
Kepustakaan
Arifianto, Alexander R. 2018. “Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?” Asian Security, https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14799855.2018.1461086, diakses pada 2 Mei 2018.
Barton, Greg dan Grey Fealy (ed.) 1996. Nahdlatul Ulama, Traditional Islam, and Modernity in Indonesia. Clayton, Australia: Monash Asia Institute.
Hadiz, Vedi. 2016. Islamic Populism in Indonesia and the Middle East. New York: Cambridge University Press.
Hamayotsu, Kikue. 2018. “Moderate-radical Coalition in the Name of Islam: Conservative Islamism in Indonesia and Malaysia,” Kyoto Review of Southeast Asia (23), https://kyotoreview.org/issue-23/conservative-islamism-indonesia-malaysia/, diakses pada 2 Mei 2018.
Hefner, Robert W. 2000. Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Hoesterey, James B. 2016. Rebranding Islam: Piety, Prosperity, and a Self-Help Guru. Stanford, CA: Stanford University Press.
Institute for Policy Analysis and Conflict (IPAC). 2018. After Ahok: The Islamist Agenda in Indonesia (6 April). Tersedia di: http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/69/After-Ahok-The-Islamist-Agenda-in-Indonesia, diakses pada 2 Mei 2018.
The Jakarta Post. 2017. “Caliphate Still Attractive to Many Students;” (1 November), http://www.thejakartapost.com/news/2017/11/01/caliphate-still-attractive-many-students-study.html, diakses pada 6 Maret 2018.
Liddle, R. William. 1996. “The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation,” Journal of Asian Studies, 55 (3): 613-634.
McBeth, John. 2017. “Widodo, His Paranoid General, and a ‘Rotting Situation’ in Indonesia,” South China Morning Post (15 Januari), http://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2062023/widodo-his-paranoid-general-and-rotting-situation-indonesia, diakses pada 2 Mei 2018.
Menchik, Jeremy. 2016. Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism. New York: Cambridge University Press.
Peterson, Daniel. 2018. “Indonesia’s Minority Report,” New Mandala (14 February), http://www.newmandala.org/indonesias-minority-report/, diakses pada 12 Maret 2018.
Pisani, Elizabeth dan Michael Buehler. 2017. “Why do Indonesian Politicians Promote Shari’a Laws? An Analytic Framework for Muslim-majority Democracies,” Third World Quarterly, 38 (3): 734-752.
Piscatori, James. 2000. Islam, Islamists, and the Electoral Principle in the Middle East. Leiden, Netherlands: ISIM. https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/10070, diakses pada 2 Mei 2018.
Qurtuby, Sumanto al. 2018. “Indonesia’s Islamist Mobilization,” Kyoto Review of Southeast Asia (23), https://kyotoreview.org/issue-23/indonesias-islamist-mobilization/, diakses pada 2 Mei 2018.
Sakai, Minako dan M. Falikul Isbah. 2014. “Limits to Religious Diversity Practice in Indonesia: Case Studies from Religious Philanthropic Institutions and Traditional Islamic Schools,” Asian Journal of Social Science, 42 (6): 722-746.
Tempo. 2017. “Liputan Khusus: Muslim Konservatif: Saleh atau Salah?” (19 – 25 Juni).
Van Bruinessen, Martin (ed.). 2013. Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn.” Singapura: Institute of Southeast Asian Studies Publishing.
Wilson, Ian D. 2015. The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority, and Street Politics. New York: Routledge.
