
“Boeat mendapat tempat dalam gemeenteraad, maka usahanja fihak kiri dalam raad itu boleh dikata berhasil. Soedara-soedara Dekker, Wiwoho, Malaka (Tan?) dan Soekindar, ialah orang-orang dari fihaknja Ra’jat, telah dapat mereboet lidmaatschap dalam Raad itoe. Hal ini nistjajalah menambah kekoeatannja partij sebelah kiri dalam gemeenteraad. Soenggoeh hal ini ada soal jang penting bagi gemeente Semarang, karena perobahan dalam samenstellingnja raadsleden ini, nistjajalah akan bisa membawa tambahnja perhatian raad akan kehinaan atoeran dalam kampoeng-kampoeng. Gemeenteraad kita jang selama ini belom boleh dikata tempat—bitjaranja Ra’jat, sekarang ini rasanja diharap akan mendjadi tempat jang tidak melengahkan kepentingannja kelas rendah.”
“Gemeenteraad Semarang”. Soeara-Ra’jat, 16 October 1921.
Uraian tentang keberhasilan golongan kiri meraih kursi di dalam pemilihan anggota dewan kota Semarang pada awal 1921 menandai satu fase penting tetapi relatif terabaikan dalam sejarah awal pergerakan antikolonial di Indonesia: keterlibatan mereka terhadap isu-isu politik perkotaan tempat mereka tinggal. Pernyataan itu membuktikan bahwa golongan kiri tidak hanya mengorganisasi demonstrasi dan pemogokan selama periode “zaman bergerak”, meminjam istilah Takashi Shiraishi (1990), tetapi juga bertarung di dalam lembaga formal kolonial seperti gemeenteraad (dewan kota). Mereka mengusung agenda politik kewargaan modern yang progresif dengan menggulirkan program kampanye seperti hak pilih universal dalam pemilihan anggota dewan kota, penghapusan sistem kapitan di perkotaan, perbaikan kampung miskin, kebijakan perumahan bersubsidi, dan lainnya.
Di kota-kota kolonial seperti Semarang dan Surabaya, aktivis Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) dan kemudian Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak menunggu munculnya kelas buruh industri yang matang. Ide-ide Marxis diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi lokal yang kompleks. Kota kolonial—meski secara fisik dan sosial sangat tersegmentasi—justru menjadi ruang penerjemahan itu: tempat bagi Marxisme ditafsir ulang untuk menghadapi kekerasan harian dari kekuasaan imperial. Dengan bersandar pada kajian di lingkungan kota kolonial Surabaya pada awal abad ke-20, tulisan ini menawarkan pembacaan ulang atas sejarah pergerakan awal abad ke-20 dengan menjadikan kota sebagai basis material perkembangan kesadaran politik progressif. [1]

Source: “De Eerste Marxisten in Indonesië”, De Waarheid, 1989.
Pertarungan Mengelola Kota (Kolonial)
Surabaya pada akhir abad ke-19 mengalami perubahan hebat sebagai bagian dari bentang kolonial Hindia Belanda yang dinamis. Pembukaan Terusan Suez pada 1869 dan diberlakukannya Kebijakan Liberal pada 1870 menandai titik balik penting yang membuka keran investasi, migrasi, dan teknologi Eropa ke kota ini. Dari kota benteng yang semula didominasi oleh garnisun militer dan struktur birokrasi, Surabaya menjelma menjadi kota industri dan perdagangan kolonial, lengkap dengan pelabuhan internasional, rel kereta api, gudang kopi dan gula, serta kompleks industri berat di wilayah utara kota. Dalam dua dasawarsa, populasi Eropa meningkat dari sekitar 4.500 jiwa pada 1870 menjadi lebih dari 10.000 pada 1890 (Von Faber, 1931)—sebuah lompatan demografis yang mencerminkan menguatnya kapitalisme kolonial di ruang perkotaan.
Pertumbuhan ekonomi tersebut menciptakan formasi sosial baru di kalangan masyarakat Eropa: hadirnya kelas menengah urban profesional seperti dokter, insinyur, guru, pengacara, pegawai swasta, dan wartawan. Mereka menyebut diri sebagai orang particulier sadja, yakni warga swasta biasa yang tidak memiliki jabatan resmi dalam birokrasi kolonial, tetapi memiliki pendidikan tinggi, pendapatan tetap, dan jaringan sosial modern. Dalam kehidupan kota, mereka aktif sebagai penggerak budaya publik: membentuk klub sosial, mendukung seni, dan menerbitkan media.
Aspirasi politik mereka tidak dibingkai oleh kekuasaan administratif, melainkan dari bawah—melalui opini, debat umum, dan mobilisasi warga. Namun, di balik dinamika itu, terdapat ketegangan yang mengakar antara kalangan partikulir dan birokrat kolonial. Kalangan partikulir menganggap para ambtenaar (pegawai negeri) sebagai penghambat kemajuan kota. Dalam pandangan mereka, birokrasi kolonial pusat di Batavia lamban, tidak peka terhadap kebutuhan lokal, dan lebih sibuk menjaga karier daripada membangun kota. Tokoh liberal seperti Adriaan Paets tot Gonsayen, seorang pengacara sukses dan pendukung gagasan liberalisme sekaligus anggota dewan kota Surabaya, bahkan menyebut sistem birokrasi di Hindia sebagai “bencana,” karena terlalu terobsesi pada karier dan prosedur, sementara kebutuhan nyata warga kota terabaikan.
Salah satu ekspresi paling konkret dari ketegangan ini terjadi pada kampanye air bersih di Surabaya. Dalam situasi wabah kolera yang berulang, terutama sepanjang 1890-an, warga Eropa kelas menengah meluncurkan kritik keras terhadap pemerintah kolonial. Melalui surat kabar Soerabajasch Handelsblad, mereka mempersoalkan buruknya sanitasi kota dan mendesak pembangunan sistem air bersih modern. Petisi yang ditujukan langsung kepada Ratu Wilhelmina ditandatangani oleh ratusan warga. Namun, pemerintah kolonial pusat tetap menunda proyek tersebut karena dianggap mahal dan tidak prioritas. Ketegangan ini memperkuat keyakinan warga kelas menengah bahwa kota harus dikelola oleh mereka yang memahami kehidupan kota, bukan oleh birokrat yang beroperasi dari Batavia.
Situasi ini mendorong munculnya aspirasi untuk membentuk tata kelola kota yang lebih otonom dan responsif. Kalangan partikulir mendorong dibentuknya gemeente (kotapraja) dan gemeenteraad (dewan kota) sebagai lembaga demokratis yang mewakili warga kota. Harapannya, lembaga ini dapat menggantikan dominasi birokrasi kolonial dengan logika pengelolaan kota yang liberal dan berbasis suara warga. Pemerintah kolonial menjawab tekanan ini melalui reformasi Desentralisasi 1903 (Decentralisatie Wet) yang memungkinkan pembentukan dewan kota di wilayah Hindia Belanda. Pada 1 April 1906, Dewan Kota Surabaya resmi berdiri dan sering dipandang sebagai tonggak penting dalam sejarah tata kelola kota modern di koloni. Namun, struktur lembaga ini tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi warga partikulir.
Dari total 15 kursi untuk anggota Eropa, delapan diisi oleh pejabat pemerintah (birokrat) dan hanya tujuh yang dipilih langsung oleh warga kota. Pemerintah kolonial juga menunjuk enam anggota tambahan dari kelompok non-Eropa: tiga dari kalangan pejabat pribumi, dan tiga lainnya dari elite Tionghoa dan Arab. Dengan kata lain, negara kolonial secara sadar membentuk struktur politik yang menjaga keseimbangan kekuasaan, agar tidak seluruhnya dikuasai oleh warga partikulir Eropa. Langkah ini mencerminkan logika kekuasaan kolonial: membuka ruang partisipasi warga kota secara terbatas, sambil tetap mengamankan otoritas negara atas ruang politik urban. Dewan Kota menjadi hasil negosiasi kompleks antara liberalisme ekonomi kelas menengah, kontrol negara kolonial, dan representasi multietnis dalam tata kelola kota.
Kaum Sosialis dan Politik Praktis
Dalam konteks itu awal perkembangan gerakan kiri di Hindia-Belanda saat itu telah tumbuh dari keyakinan bahwa untuk mewujudkan gagasan ideal politik mereka di ruang publik, berpartisipasi di dalam lembaga dewan kota adalah satu langkah strategis yang penting. Di Semarang, misalnya, Westerveld yang kemudian menjadi anggota ISDV dan anggota dewan kota Semarang aktif mengkampanyekan arti penting pemerintahan kota dan tatakelola pertanahan. Ia mengusulkan agar pemerintah kota harus memiliki sebuah “rencana perkembangan kota dengan membeli lahan-lahan permukiman untuk mencegah spekulasi harga tanah”: “Lahan-lahan hanya bisa disewakan dan tidak diperjualbelikan” yang menjadi landasan program pembangunan perumahan rakyat (Een Gemeentelijke Grondpolitiek, 1912).
Sementara di Surabaya, beberapa pegiat sosialis seperti L.D.J Reeser (kelak menjadi ketua ISDV) dan Mr. Van Ravensteyn, turut aktif dalam proses pembentukan Dewan Kota Surabaya. Masing-masing bertindak sebagai ketua dan sekretaris Komite Pemilihan (Verkiezingscomité) yang dibentuk pada Januari 1906. Langkah penting mereka adalah memperluas cakupan politik lokal agar tidak hanya menjadi milik eksklusif elite Eropa. Mereka membuka ruang partisipasi bagi perempuan—yang meskipun belum memiliki hak pilih resmi tetap diundang hadir dalam rapat umum—dan mengundang perwakilan dari kalangan pribumi, Tionghoa, dan Timur Asing untuk menyampaikan pandangan mereka. Dalam hal ini, politik dewan kota menjadi wahana strategis bagi kaum sosialis untuk memperjuangkan gagasan kewargaan modern, yang melampaui sekat rasial dan gender dalam masyarakat kolonial. Namun dalam pemilihan resmi wakil-wakil Eropa untuk duduk di Dewan Kota, Reeser dan van Ravensteyn kalah bersaing dari calon-calon yang berasal dari kalangan pengusaha, industrialis, dan elite bisnis konservatif. Bagi warga Eropa yang mencari penghidupan di koloni dan menempati posisi kelas menengah, perwakilan sosialis bukanlah sesuatu yang mereka hendaki.
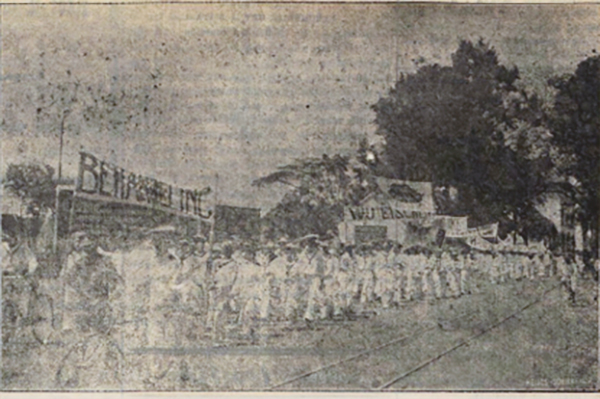
Source: Preanger Bode, May 17, 1916.
Partisipasi golongan kiri dalam politik kota baru dimulai seiring dengan proses pembentukan ISDV dan keputusan terlibat dalam “politik praktis” saat pembentukan ISDV pada akhir 1914 (Perthus, 1976). Apa yang dimaksud dengan politik praktis dalam keputusan tersebut adalah upaya terlibat dalam pertarungan mendapatkan kursi di dalam dewan kota yang telah dibentuk sejak awal abad itu. Bagaimanapun ini bukan sebuah pertarungan yang mudah.
Kerjasama politik antara Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) dan Insulinde menjadi kendaraan penting dalam upaya tersebut. Dalam kampanye pemilihan anggota dewan kota pada Juni 1914, keduanya mengusung C. Hartogh, pemimpin ISDV Surabaya, sebagai calon utama. Koalisi ini menyusun platform kampanye bersama yang mereka sebut sebagai “Sociale Gemeentepolitiek”—sebuah politik kotapraja yang berorientasi sosial. Program ini mengangkat dua isu utama yang mencerminkan agenda sosialis progresif dalam tata kelola kota kolonial: perluasan hak pilih bagi warga pribumi dan politik pertanahan milik kota (gemeentegrond).
Dalam isu pertama, fraksi sosialis menyerukan agar pemerintah kolonial membuka ruang partisipasi politik bagi kalangan pribumi terpelajar dan kelas menengah yang telah dianggap layak berpartisipasi dalam politik modern. Mereka mengkritik sistem perwakilan dalam Dewan Kota yang masih didominasi oleh penunjukan, bukan pemilihan, bagi wakil pribumi. Dengan dukungan dari sedikitnya 60 pemilih pribumi di Surabaya—jumlah yang relatif tinggi untuk ukuran kota kolonial—fraksi ini berharap dapat memperluas basis dukungan mereka di luar komunitas Eropa.
Isu kedua yang mereka angkat adalah soal pengelolaan tanah milik kotapraja. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah kota yang menjual tanah-tanah strategis seperti di Gubeng Utara kepada instansi kolonial seperti Jawatan Kereta Api Negara untuk keperluan infrastruktur negara, alih-alih memanfaatkannya untuk kepentingan umum, seperti membangun kompleks perumahan rakyat yang sangat dibutuhkan oleh warga kota, khususnya kaum buruh dan masyarakat kelas bawah.
Dalam arena pemilihan Dewan Kota, koalisi ISDV-Insulinde berhasil mengungguli kekuatan politik lain seperti Kiesvereeniging Soerabaja (Perkumpulan Pemilih Surabaya), Partai Etis Kristen (Christelijk-Etisch Partij/CEP), dan Partai Liberal (Indischen Vrijzinnig Bond). Kemenangan ini memungkinkan mereka membentuk fraksi sosialis di dalam Dewan Kota Surabaya, menjadikan kota ini sebagai satu-satunya basis politik lokal di Hindia Belanda saat itu yang memiliki representasi formal kekuatan kiri. Sebaliknya, di Semarang, usaha serupa untuk mengangkat Sneevliet ke kursi dewan kota gagal karena lemahnya jumlah pemilih pribumi. Meski fraksi sosialis di Surabaya tergolong kecil dan belum cukup kuat untuk mendominasi arah kebijakan kota, mereka berhasil menancapkan agenda-agenda sosial mereka ke dalam ruang formal politik kolonial.
Golongan Kiri dan Krisis
Pada tahun-tahun menjelang dan selama 1918 krisis ekonomi dunia menghampiri Hindia. Fraksi kiri memandang pentingnya intervensi pemerintah kota menghadapi situasi krisis tersebut. Fraksi sosialis di Dewan Kota, yang dibentuk dari aliansi antara ISDV dan Insulinde, mulai merumuskan program-program kebijakan yang secara jelas mewakili agenda sosialisme perkotaan. Dipimpin oleh C. Hartogh, fraksi ini mendorong dua usulan utama: pembangunan rumah murah bagi masyarakat kelas bawah dan penetapan harga maksimum atas kebutuhan pokok, termasuk sewa rumah dan bahan bangunan. Usulan ini lahir dari situasi krisis yang mendera kota selama Perang Dunia I, ketika pasokan dari Eropa terganggu, populasi Eropa yang bertahan di koloni meningkat, dan harga-harga melonjak drastis. Studi pemerintah menyebut bahwa pada 1918, Surabaya kekurangan 4.000 unit rumah dan harga sewa rumah melonjak tajam hingga mencapai dua kali lipat dari harga sebelum perang.
Melihat kondisi itu, Hartogh menggagas pembentukan Woningbedrijf (perusahaan perumahan kota) dan Grondbedrijf (perusahaan pengelola tanah) untuk menanggulangi spekulasi pasar properti. Ia bahkan membentuk Woningvereeniging bersama Jos M. Suijs dari Christelijk Etisch Partij dan D. Williams dari Insulinde, untuk memastikan pembangunan rumah sesuai dengan kebutuhan keluarga kelas buruh.
Meski program ini secara resmi disetujui dan dijalankan pemerintah kota—dengan pinjaman besar dari Java Bank dan penerbitan obligasi jutaan gulden—penerapannya tetap dibayangi oleh batas-batas rasial dalam masyarakat kota kolonial. Rumah murah ini utamanya menyasar kalangan Indo-Eropa berpenghasilan rendah, bukan buruh pribumi yang menghadapi krisis dengan cara berbeda.
Selain isu perumahan, fraksi kiri di dewan juga menaruh perhatian besar terhadap krisis pangan. Pada Februari 1918, Hartogh menggulirkan mosi untuk penetapan harga maksimum kebutuhan pokok, termasuk beras. Ia memperingatkan tentang “parade kelaparan” yang mulai tampak di jalan-jalan kota, dan menyatakan bahwa jika dewan tidak bertindak, maka ia akan membawa perjuangan ke luar dewan. Pemerintah merespons dengan mendirikan dapur umum dan membeli beras dengan subsidi, serta membangun gudang pangan. Namun, penyelidikan menunjukkan adanya permainan harga oleh kongsi-kongsi dagang Tionghoa, yang menyebabkan harga beras melonjak jauh melebihi harga di Batavia atau Semarang.
Krisis ini membuka ruang kerjasama antara politik kiri Eropa dan aktivisme pribumi. Pada 1919, Hartogh bersama Rosenquist dari Sarekat Hindia dan Soekiran dari Sarekat Islam mengajukan usulan bersama untuk pengawasan distribusi beras. SI bahkan mengorganisir rapat umum yang dipimpin Muso, sekretaris CSI dan redaktur Oetoesan Hindia, yang menuntut dilibatkannya organisasi rakyat dalam pengelolaan pasokan pangan.
Perbedaan tanggapan terhadap krisis ini mencerminkan basis sosial dan rasial yang berbeda pula. Warga Indo dan Eropa kelas menengah bawah lebih peduli pada isu sewa rumah dan kualitas lingkungan hidup, sementara bagi mayoritas warga pribumi, krisis pangan jauh lebih mendesak dan tak terhindarkan. Maka, jika agenda sosialisme perkotaan yang diusung Hartogh lahir dari kebutuhan kalangan Eropa dan Indo, dukungan SI terhadap pengawasan pasar beras menunjukkan bahwa politik kiri di Surabaya bergerak dengan pemahaman mendalam atas realitas sosial kolonial yang tersegregasi.
Meski popularitas program sosial fraksi kiri meningkat, batasan sistem pemilihan yang berbasis ras membuat politik kiri tidak sepenuhnya mampu mengubah bentang kekuasaan kota. Hartogh bahkan gagal terpilih kembali dalam pemilihan 31 Juli 1918 setelah ISDV memutus koalisi dengan Insulinde dan mendekat ke SI. Ia kalah tipis karena pemilih pribumi—meskipun merupakan mayoritas penduduk kota—hanya memiliki 78 suara resmi dalam sistem elektoral kota, sedangkan suara mayoritas tetap dikuasai oleh pemilih Eropa dan Indo yang tidak selalu berpihak pada agenda sosialis ISDV. Politik kiri di kota kolonial berjalan di antara celah sempit: aktif di dalam dewan, membangun program konkret, tetapi terus dihadapkan pada batasan struktural yang ditetapkan oleh sistem kolonial yang menyeleksi siapa yang dianggap sebagai warga penuh dan siapa yang sekadar penduduk yang dibebani pajak. Meski demikian, jejak politik kiri di Surabaya memperlihatkan kemungkinan lain dalam politik kolonial, yakni: sebuah upaya membangun keadilan sosial dalam ruang kota yang timpang.
Penutup
Dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, narasi besar yang sering diangkat cenderung menekankan pada tokoh-tokoh nasionalis dan organisasi-organisasi moderat yang lahir dari lingkaran elite terpelajar. Akibatnya, jejak penting kaum kiri—khususnya golongan sosialis dan komunis—sering kali terpinggirkan atau diciutkan hanya pada fase radikalisasi politik pasca-1926. Padahal, sejak awal abad ke-20, kaum kiri di Hindia Belanda telah memainkan peran penting dalam membentuk medan politik baru, khususnya di tingkat kota. Kisah mereka bukan hanya soal agitasi atau pemberontakan, tetapi juga tentang perjuangan membangun bentuk tata kelola kota yang lebih adil, demokratis, dan berpihak pada rakyat kecil—agenda yang sangat progresif untuk konteks kolonial saat itu.
Surabaya menjadi contoh nyata bahwa politik kiri tidak berhenti pada wacana atau doktrin, tetapi diterjemahkan dalam bentuk kebijakan sosial konkret. Melalui Dewan Kota, mereka mendorong pembangunan rumah murah, pengendalian harga bahan pokok, dan pengelolaan tanah untuk kepentingan umum. Aktivias politik praktis golongan kiri di tengah masyarakat kolonial yang terstruktur oleh ras dan kelas memberikan gambaran menarik tentang langkah menembus batas-batas eksklusi dan menyusun bentuk awal dari apa yang bisa disebut sebagai “politik kewargaan kota” (urban citizenship). Politik kiri di Surabaya mengusulkan bahwa hak atas kota bukan hanya milik warga Eropa, pengusaha, atau birokrat, tetapi juga milik buruh, orang Indo, dan bahkan masyarakat pribumi yang dibebani pajak tetapi tidak memiliki suara.
Sayangnya, peran ini jarang mendapat tempat yang layak dalam historiografi arus utama sejarah Indonesia. Politik kiri hanya dikenang dalam kaitan dengan pemberontakan atau represi, bukan atas sumbangsihnya terhadap pembangunan gagasan tentang demokrasi, kewargaan, dan keadilan sosial dalam ruang kota. Sejarah awal praktik politik gerakan kiri menunjukkan agenda penting bagaimana membayangkan dan mewujudkan tata hidup bersama yang lebih adil dalam keseharian masyarakat kota yang bersinggungan dengan kebutuhan sehari-hari warga biasa.
Andi Achdian
Kepala Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional
[1] Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang telah diterbitkan. Simak Andi Achdian, Ras, Kelas Bangsa: politik pergerakan antikolonial di Surabaya abad ke-20 (Tangerang: Marjin Kiri, 2023).
